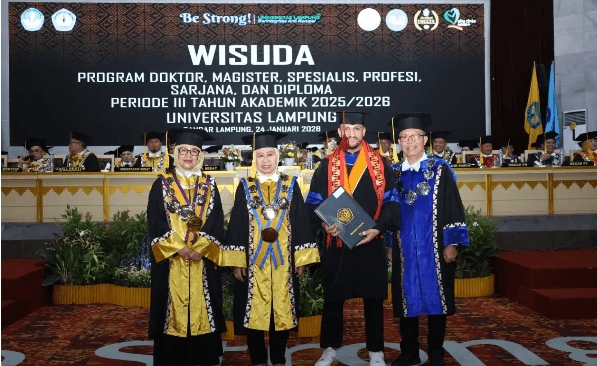KADANG kita bangga sudah bisa baca tulis, tapi lupa satu hal, yaitu literasi itu bukan cuma huruf, tapi cara berpikir.
Semua orang sekarang bisa mengetik status panjang di media sosial, namun belum tentu mereka paham isi tulisannya sendiri.
Pepatah lama bilang, “Tajam pisau karena diasah, tajam akal karena dibaca”. Tapi membaca di sini bukan cuma di buku melainkan membaca situasi, membaca orang, dan membaca makna.
Di Festival Literasi Sumsel 2025 inilah Gubernur H. Herman Deru baru -baru ini datang, bukan cuma untuk memotong pita dan tersenyum ke kamera. Ia datang sembari “menyentil halus” lewat pidato yang lebih berisi dari sekadar seremoni.
Deru menegaskan, literasi tak berhenti pada kemampuan membaca dan menulis, tapi juga soal memahami konteks komunikasi.
Kalimatnya memang sederhana, tapi kalau direnungkan, rasanya kayak dicubit pelan, tapi kena dihati, apalagi di negeri ini, banyak yang bisa bicara, tapi tak banyak yang benar-benar bisa menyampaikan pesan.
Deru juga, menyinggung soal pembicara yang gagal membaca suasana. Nah, ini sindiran yang kena banget.
Sering kali audiens kabur bukan karena ruangan panas, tapi karena isi pidato dingin tanpa arah.
Bukannya tercerahkan, malah pengen kabur lebih cepat dari sinyal WiFi yang ngadat.
Pesan literasi Sumsel, jadi terasa penting di sini, sebab literasi itu bukan soal banyak bicara, tapi soal tahu kapan dan bagaimana bicara.
Karena sejatinya, literasi adalah jembatan antara logika dan empati.
Kalau cuma logika tanpa empati, jadinya debat kusir. Tapi kalau empati tanpa logika, bisa-bisa percaya hoaks tiap lima menit.
Lihat saja Finlandia atau Jepang. Negara-negara itu maju bukan karena rakyatnya doyan baca novel seribu halaman dari subuh sampai tidur, tapi karena sejak kecil mereka belajar berpikir kritis dan berdiskusi dengan sopan.
Anak-anak di sana tahu bedanya pendapat dan fakta. Kalau mereka debat, ujungnya bukan adu volume suara, tapi adu data dan akal sehat.
Melek huruf, belum tentu melek makna
Bayangkan kalau semangat seperti itu menular ke literasi Sumsel.
Bisa-bisa festival literasi bukan cuma acara tahunan, tapi gaya hidup baru, ngobrol di warung kopi sambil tukar data, bukan tukar gosip.
Indonesia nggak kekurangan orang cerdas, tapi sering kesulitan menyampaikan gagasan dengan cerdas pula.
Birokrat hobi pakai jargon, warga sibuk debat di kolom komentar, tapi jarang ada ruang buat benar-benar memahami.
Nah, di sinilah Festival Literasi Sumsel seharusnya nggak berhenti di lomba baca puisi dan sambutan berjam-jam.
Festival ini perlu hidup sebagai gerakan sosial yang bikin cara berpikir dan berkomunikasi kita ikut berubah.
Bandung bisa jadi contoh. Pemerintahnya nggak cuma bangun perpustakaan megah, tapi juga taman baca di taman kota, di kafe, bahkan di warung kopi.
Mereka bikin literasi terasa santai, dekat, dan keren.
Kalau Sumsel mau meniru, mulai dari hal kecil, buka pojok baca di Kantor Lurah, bikin klub menulis di sekolah, atau dorong anak muda bikin podcast lokal di desa.
Karena literasi sejati tumbuh dari kebiasaan, bukan dari seremoni.
Pada akhirnya, literasi bukan cuma soal pengetahuan, tapi juga soal kesadaran.
Kita bisa punya seribu buku, tapi tanpa keinginan memahami, sama saja seperti menatap rak buku sambil bangga merasa pintar.
Bangsa yang melek huruf belum tentu melek makna.
Dan kalau kita cuma sibuk membaca tanpa mengerti, rasanya seperti nonton film tanpa subtitle rame, tapi nggak nyambung.
Jadi, sebelum sibuk membagikan kutipan bijak di media sosial, mari baca diri sendiri dulu.
Karena kadang, yang paling sulit dibaca bukan novel tebal, tapi hati dan logika kita sendiri.
Festival Literasi Sumsel 2025 memberi pesan penting, literasi bukan cuma urusan buku, tapi urusan hidup.
Pemerintah perlu terus menyalakan gerakan literasi sampai ke desa, bukan lewat baliho dan seremoni, tapi lewat kebiasaan nyata.
Sebab literasi sejati tak hanya mencerdaskan pikiran, tapi juga menenangkan hati.
Dan bangsa yang bisa membaca dengan makna, itulah bangsa yang benar-benar maju. [***]